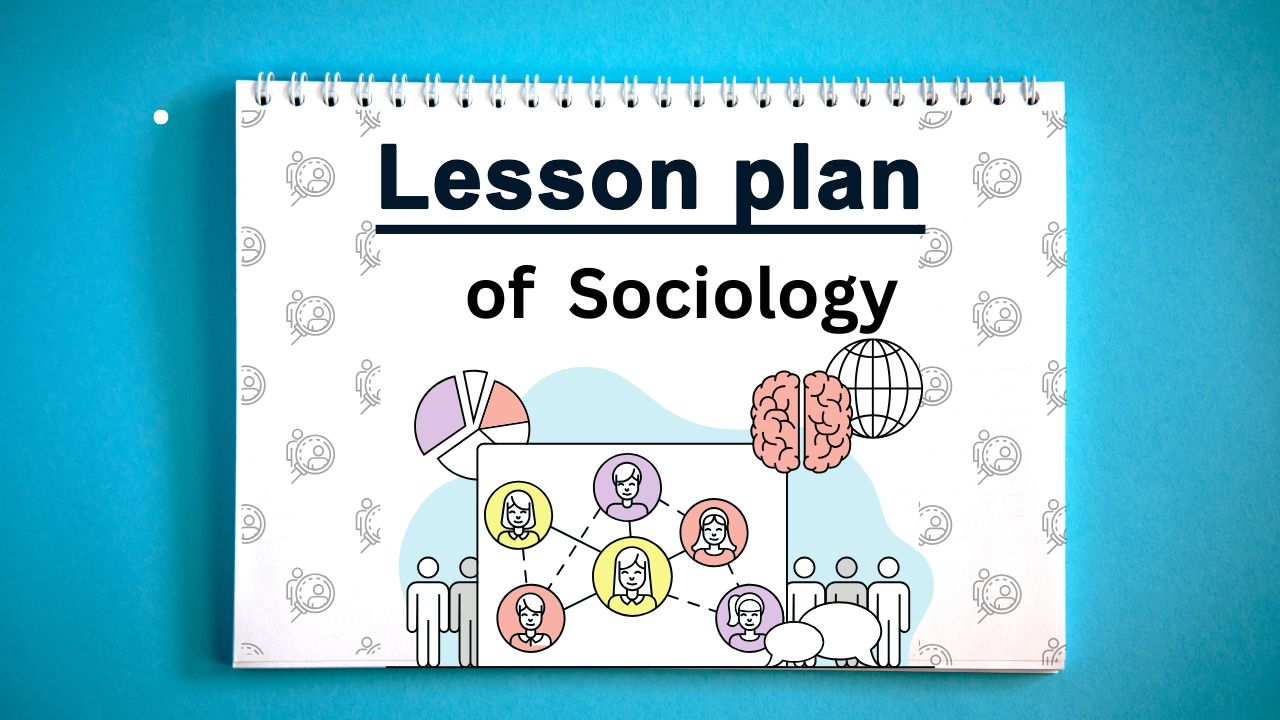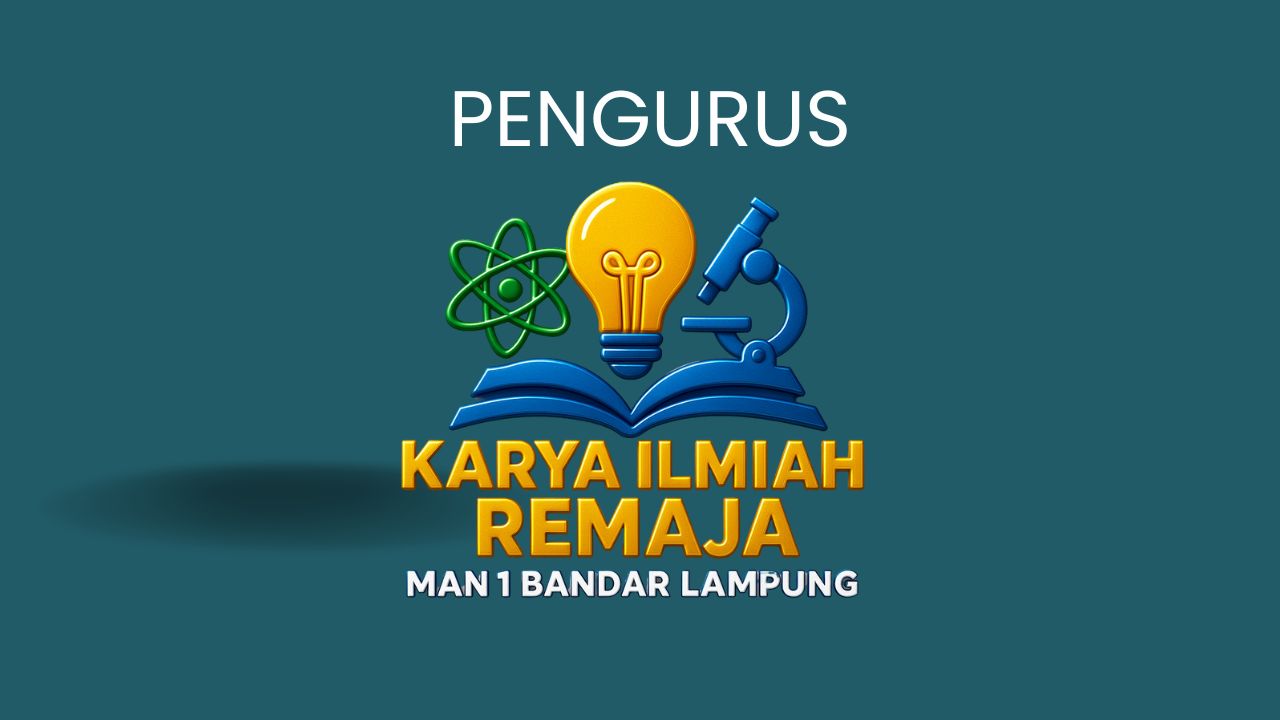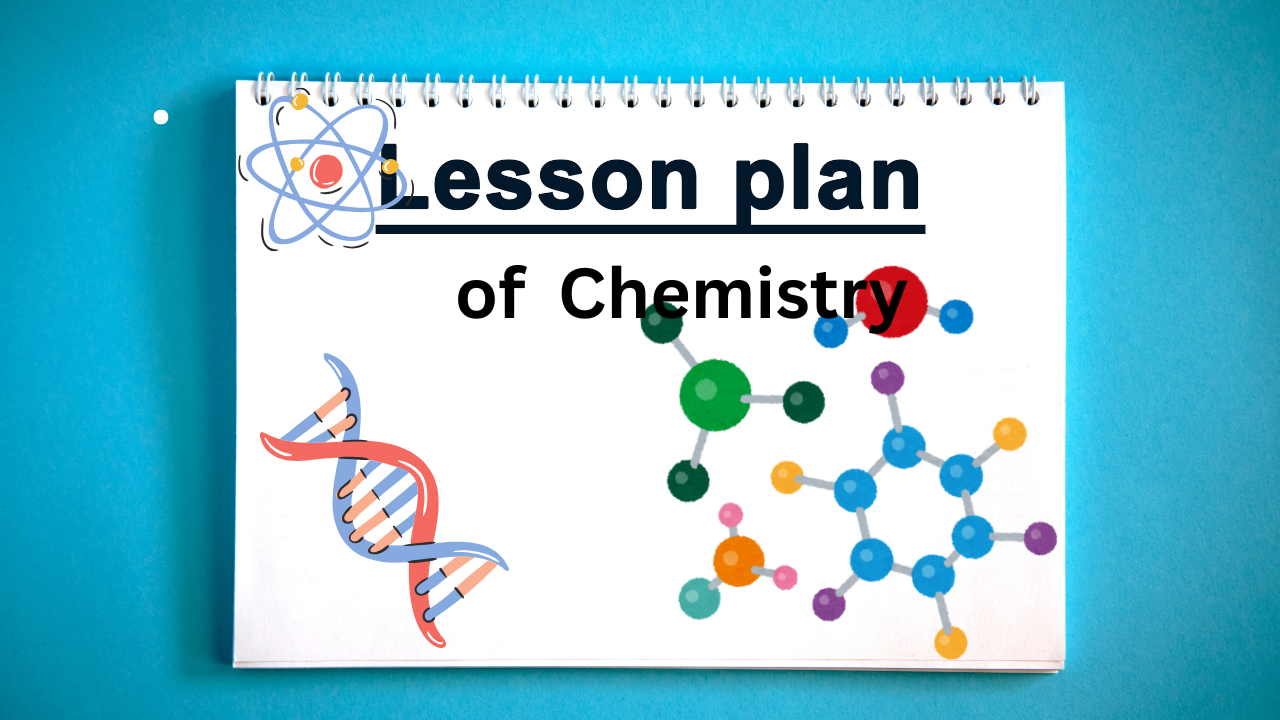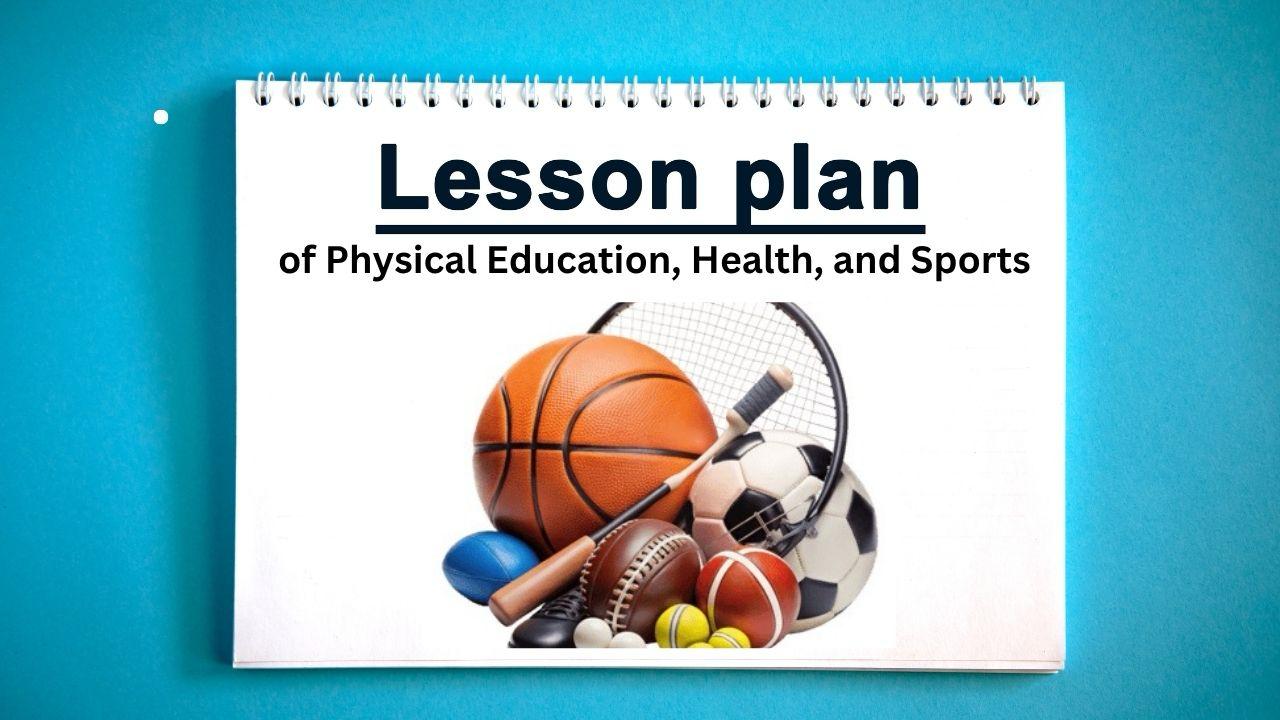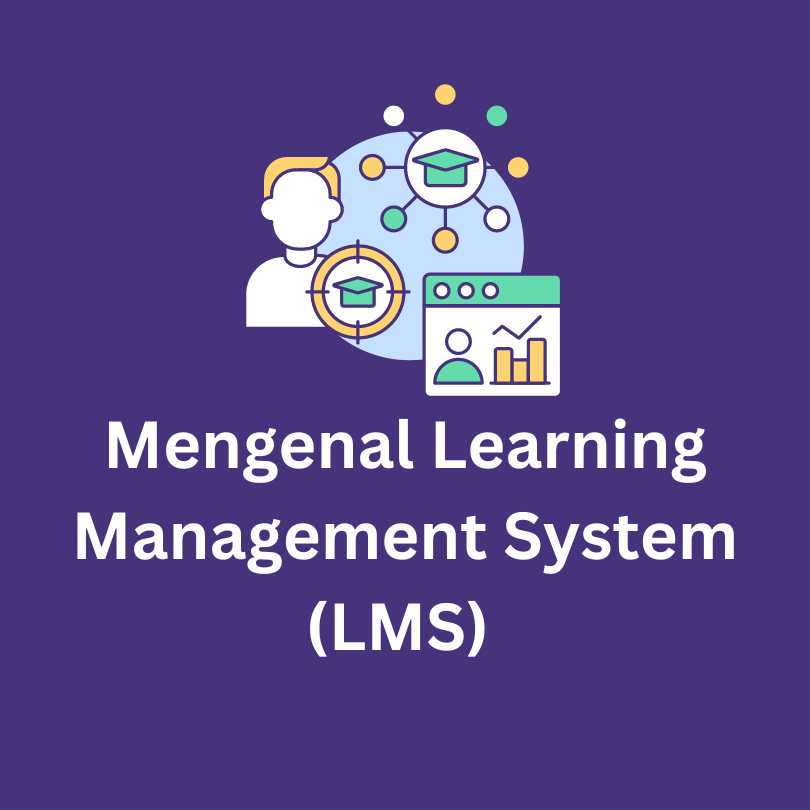|
Perencanaan Pembelajaran Sosiologi 2
Definisi, Objek Kajian, dan Fungsi Sosiologi
|
| Nama Penyusun |
Fatkhurohmah,S.Pd |
| Sekolah |
MAN 1 Bandar Lampung |
| Tahun Ajaran/Semester |
2025-2026/1 |
| Mata Pelajaran |
Sosiologi |
| Jenjang |
Madrasah Aliyah |
| Kelas |
X (Sepuluh) |
| Alokasi waktu |
2 Pertemuan (4 x 45 menit JP) |
| Tahapan |
Fase E |
| Konten Utama |
Definisi, Objek Kajian, dan Fungsi Sosiologi |
| Identifikasi Kesiapan Murid |
- Pengetahuan Awal: Murid umumnya memiliki pemahaman umum tentang “masyarakat” dan “interaksi sosial” dari pengalaman sehari-hari mereka. Mereka mungkin pernah mendengar istilah “sosiologi” tetapi belum memahami secara mendalam apa itu sosiologi, apa yang dipelajarinya, atau mengapa ilmu ini penting. Mereka mungkin sudah sering melihat fenomena sosial di lingkungan sekitar atau di media massa (misalnya, tawuran, tren gaya hidup, kasus korupsi), tetapi belum mampu menganalisisnya dari sudut pandang sosiologis.
- Minat: Minat murid bisa bervariasi. Beberapa mungkin sangat tertarik pada isu-isu sosial kontemporer (media sosial, bullying, kesenjangan sosial), sementara yang lain mungkin belum melihat relevansi sosiologi dalam kehidupan mereka. Memulai dengan contoh-contoh nyata yang dekat dengan pengalaman mereka dapat membangkitkan minat.
- Latar Belakang: Murid berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial akan menjadi modal awal untuk memahami konsep-konsep sosiologi. Beberapa mungkin berasal dari keluarga yang aktif di organisasi masyarakat, sementara yang lain lebih individual.
- Kebutuhan Belajar:
- Visual: Membutuhkan banyak contoh gambar/video fenomena sosial, diagram konsep, infografis definisi tokoh.
- Auditori: Membutuhkan penjelasan yang jelas, diskusi kelompok, presentasi, dan mendengar studi kasus.
- Kinestetik: Membutuhkan aktivitas bermain peran (role-play), observasi sederhana di lingkungan sekolah, atau proyek pengamatan interaksi sosial.
- Diferensiasi: Perlu adanya variasi dalam jenis contoh kasus yang diberikan, tingkat kompleksitas analisis, dan cara menyajikan hasil pemahaman untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan tingkat pemahaman.
|
| Karakteristik Materi Pelajaran |
- Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai:
- Konseptual: Pemahaman tentang definisi sosiologi dari berbagai ahli, ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu, objek kajian sosiologi (masyarakat, interaksi sosial, gejala sosial), dan fungsi sosiologi (pembangunan, penelitian, pemecahan masalah).
- Prosedural: Kemampuan mengidentifikasi gejala-gejala sosial di lingkungan sekitar, menganalisisnya dari sudut pandang sosiologi, dan merumuskan contoh fungsi sosiologi dalam kehidupan nyata.
- Metakognitif: Kesadaran akan pentingnya memahami sosiologi untuk melihat dunia secara lebih objektif, mengembangkan empati, dan menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dalam masyarakat.
- Relevansi dengan Kehidupan Nyata Murid:
- Membantu murid memahami dinamika pergaulan di sekolah, di lingkungan rumah, dan di media sosial.
- Mengembangkan kemampuan menganalisis isu-isu sosial yang sedang viral atau terjadi di masyarakat (misalnya, mengapa suatu tren bisa populer, mengapa terjadi konflik, bagaimana dampak media sosial).
- Membekali murid dengan perspektif untuk menjadi warga negara yang kritis dan berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial.
- Membantu mereka memahami diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat.
- Tingkat Kesulitan: Materi ini memiliki tingkat kesulitan sedang. Konsep dasarnya cukup mudah dipahami, tetapi mengaplikasikan konsep tersebut untuk menganalisis fenomena sosial secara mendalam membutuhkan kemampuan abstraksi dan penalaran yang cukup baik. Perbedaan definisi sosiologi dari berbagai ahli juga perlu ketelitian.
- Struktur Materi: Materi akan disajikan secara berurutan: dimulai dari pemahaman mengapa sosiologi itu ada (sejarah singkat), kemudian definisi sosiologi, dilanjutkan dengan objek kajian sosiologi, dan diakhiri dengan fungsi sosiologi dalam berbagai aspek kehidupan.
- Integrasi Nilai dan Karakter:
- Kewargaan: Mengembangkan kesadaran sebagai bagian dari masyarakat, peduli terhadap masalah sosial.
- Penalaran Kritis: Menganalisis fenomena sosial secara objektif, tidak mudah menghakimi, mencari akar permasalahan.
- Kolaborasi: Bekerja sama dalam diskusi dan proyek analisis fenomena sosial.
- Empati: Memahami perspektif dan pengalaman orang lain dalam konteks sosial.
- Tanggung Jawab: Terhadap peran sebagai anggota masyarakat dan dalam upaya penyelesaian masalah sosial.
- Komunikasi: Menyampaikan hasil analisis fenomena sosial secara jelas.
- Keimanan dan Ketakwaan: Mengagumi kompleksitas ciptaan Tuhan dalam bentuk masyarakat dan interaksi sosial.
|
| Dimensi Profil Lulusan |
Dimensi lulusan pembelajaran yang akan dicapai adalah:
- Kewargaan: Murid memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat serta mampu memahami berbagai dinamika sosial.
- Penalaran Kritis: Murid mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi gejala-gejala sosial di sekitarnya dengan menggunakan perspektif sosiologi.
- Kolaborasi: Murid mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mengamati, menganalisis, dan mempresentasikan fenomena sosial.
- Komunikasi: Murid mampu menyampaikan ide dan hasil analisis tentang fenomena sosial secara jelas dan efektif, baik lisan maupun tulisan.
- Kemandirian: Murid mampu mencari informasi mandiri tentang isu-isu sosial dan mengembangkan pemahaman pribadi tentang sosiologi.
|
| Dimensi Kurikulum Berbasis Cinta |
- Cinta pada Keaslian Diri
- Cinta pada Keterbukaan dan Penghargaan
- Cinta pada Kehidupan & Kemanusiaan
|
| Insersi Materi KBC |
- menekankan pentingnya mengenali dan menerima diri apa adanya.
- Murid belajar bahwa setiap orang mengekspresikan identitasnya secara berbeda dan itu patut dihargai.
- identitas diri tidak hanya untuk kebanggaan pribadi, tapi juga harus diwujudkan dalam sikap positif di masyarakat.
- murid diajak untuk jujur, objektif, dan reflektif dalam menyusun laporan.
- murid belajar menyampaikan pemikiran dengan percaya diri, terbuka, dan menghargai audiens.
|
| Capaian Pembelajaran |
Pada akhir Fase E, murid memahami konsep dasar berbagai bidang ilmu sosial sebagai ilmu yang mengkaji manusia dan lingkungannya untuk memberikan landasan berpikir kritis, analitis, kreatif, adaptif, dan solutif dalam merespons peristiwa dan fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dalam lingkup lokal, nasional, dan global. Murid memahami peran dan potensi dirinya dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Murid secara mandiri maupun berkolaborasi menggali fenomena kehidupan manusia secara sistematis serta menemukan persamaan dan perbedaannya dalam dimensi ruang dan waktu. Murid menganalisis, menarik simpulan, mengomunikasikan informasi dan hasil analisis dari sumber primer dan/atau sekunder, hasil observasi dan dokumentasi. Murid mampu merefleksikan hasil analisis dari informasi, hasil observasi, dan hasil dokumentasi, serta menyusun rencana tindak lanjut. |
| Lintas Disiplin Ilmu |
- Antropologi: Studi tentang kebudayaan dan masyarakat, memberikan konteks bagi pemahaman gejala sosial.
- Ekonomi: Dampak perilaku ekonomi terhadap masyarakat, masalah kemiskinan, kesenjangan, dan konsumsi.
- Sejarah: Memahami konteks historis perkembangan masyarakat dan fenomena sosial.
- Geografi: Keterkaitan antara aspek geografis dan pola-pola sosial masyarakat.
- Psikologi: Aspek individu dalam interaksi sosial, perilaku kelompok.
- Ilmu Komunikasi: Proses interaksi sosial, peran media dalam membentuk opini dan perilaku sosial.
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Konsep hak dan kewajiban warga negara, partisipasi sosial, nilai-nilai luhur bangsa.
- Statistika/Matematika: Pengolahan data sosial sederhana (misalnya, persentase remaja yang menggunakan media sosial tertentu).
|
| Tujuan Pembelajaran |
Pertemuan 1: Pengertian dan Objek Kajian Sosiologi (2 JP)
- Melalui pengamatan video/gambar fenomena sosial dan diskusi kelas, murid mampu menjelaskan mengapa sosiologi penting untuk dipelajari dalam memahami kehidupan sehari-hari (C2).
- Melalui studi literatur dan diskusi kelompok, murid mampu membandingkan berbagai definisi sosiologi menurut para ahli (misalnya, August Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Pitirim Sorokin) dengan cermat (C4).
- Melalui pengamatan lingkungan sekolah atau analisis studi kasus, murid mampu mengidentifikasi objek kajian sosiologi (masyarakat, interaksi sosial, gejala sosial) dan memberikan contoh konkret dari masing-masing objek kajian tersebut (C3).
Pertemuan 2: Ciri-Ciri dan Fungsi Sosiologi (2 JP)
- Melalui diskusi kelompok dan analisis contoh-contoh kasus, murid mampu mengidentifikasi ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan (empiris, teoretis, kumulatif, non-etis) dan menjelaskan implikasinya dalam penelitian sosial (C3).
- Melalui studi kasus masalah sosial kontemporer (misalnya, isu sampah di Tegal, maraknya berita bohong, masalah pengangguran), murid mampu menganalisis fungsi sosiologi dalam pembangunan, penelitian, dan pemecahan masalah sosial di tingkat lokal maupun nasional (C4).
- Melalui presentasi dan refleksi, murid mampu merumuskan peran sosiologi dalam membentuk warga negara yang kritis, peka, dan bertanggung jawab terhadap masalah sosial di lingkungan sekitar mereka (P5).
|
| Topik Pembelajaran Kontekstual |
- Fenomena “Citayam Fashion Week” atau tren media sosial lainnya: Mengapa bisa viral? Siapa yang memengaruhinya?
- Masalah sampah di lingkungan sekolah/kota Bandar Lampung: Mengapa sulit diatasi? Bagaimana peran masyarakat?
- Penggunaan bahasa daerah (Bahasa Lampung) di kalangan remaja: Mengapa ada yang masih mempertahankan, ada yang tidak?
- Perilaku pengendara di jalan raya Bandar Lampung: Mengapa sering terjadi pelanggaran?
- Dampak kehadiran warung kopi/kafe kekinian terhadap interaksi sosial remaja di Bandar Lampung.
|
| Kerangka Pembelajaran |
- Praktik Pedagogik
- Model Pembelajaran: Discovery Learning, Problem-Based Learning (PBL), Project-Based Learning (PBL) untuk proyek observasi sosial sederhana.
- Strategi Pembelajaran:
- Mindful Learning: Dimulai dengan aktivitas “Mindful Observation” (misalnya, mengamati interaksi teman sebaya di kelas atau di kantin selama 1 menit tanpa berbicara) untuk meningkatkan kesadaran terhadap pola-pola sosial. Pertanyaan reflektif yang merangsang pemikiran mendalam tentang “mengapa kita berperilaku demikian?”.
- Meaningful Learning: Mengaitkan konsep-konsep sosiologi dengan isu-isu sosial aktual yang sedang hangat di media massa atau yang relevan dengan kehidupan sehari-hari murid. Pembelajaran berbasis masalah yang menantang murid untuk menganalisis dan mencari solusi.
- Joyful Learning: Penggunaan media pembelajaran yang interaktif (video pendek, infografis, kuis interaktif). Permainan peran (role-play), studi kasus yang menarik, dan kegiatan observasi yang memicu rasa ingin tahu. Diskusi yang dinamis dan mendorong partisipasi aktif.
- Metode Pembelajaran:
- Diskusi kelompok dan pleno
- Studi kasus (analisis fenomena sosial)
- Simulasi/role-play
- Observasi sederhana
- Penugasan proyek (laporan observasi singkat)
- Presentasi
- Tanya jawab
- Kuis interaktif
- Kemitraan Pembelajaran
- Lingkungan Sekolah: Guru Bimbingan Konseling (BK) (untuk isu-isu sosial di sekolah), Guru PPKn (untuk nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan), Guru Sejarah (untuk konteks perkembangan masyarakat), Kemuridan (untuk data masalah sosial di sekolah).
- Lingkungan Luar Sekolah: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial (misalnya, LSM anak, lingkungan, pemberdayaan masyarakat), Dinas Sosial, tokoh masyarakat/pemuka adat setempat (sebagai narasumber untuk fenomena lokal).
- Masyarakat: Mengajak orang tua untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial di lingkungan tempat tinggal.
- Lingkungan Belajar
- Ruang Fisik: Kelas yang nyaman dengan akses ke proyektor/layar. Area yang fleksibel untuk diskusi kelompok dan presentasi. Lingkungan sekolah (kantin, lapangan, taman) sebagai objek observasi.
- Ruang Virtual: Pemanfaatan Learning Management System (LMS) seperti Google Classroom untuk distribusi materi, pengumpulan tugas, dan forum diskusi asinkron. Penggunaan platform video conference (Google Meet/Zoom) untuk sesi daring atau menghadirkan narasumber dari luar.
- Budaya Belajar:
- Budaya berpikir kritis dan analitis terhadap fenomena sosial.
- Budaya empati dan saling menghargai perbedaan.
- Budaya kolaborasi dan berbagi perspektif.
- Budaya peka terhadap masalah sosial di sekitar.
- Penggunaan teknologi secara etis untuk riset sosial.
- Pemanfaatan Digital
- Perpustakaan Digital: Mengarahkan murid ke jurnal ilmiah sosial daring, situs berita terpercaya (misalnya, Kompas.com, Detik.com bagian sosial), atau platform data statistik sosial (misalnya, BPS).
- Forum Diskusi Daring: Google Classroom atau platform lain untuk diskusi asinkron, berbagi tautan video/artikel berita tentang fenomena sosial, dan mengumpulkan ide.
- Penilaian Daring: Google Forms untuk kuis, Kahoot/Mentimeter untuk kuis interaktif, Jamboard untuk curah pendapat.
- Multimedia: Menonton video dokumenter sosial, film pendek tentang isu sosial, infografis tentang data sosial.
- Media Sosial: Sebagai objek kajian dan sumber informasi (dengan bimbingan dan filter yang ketat).
|
| Langkah-langkah Pembelajaran |
Kegiatan Pendahuluan (Mindful Learning, Joyful Learning):
- Pembukaan & Kesadaran (Mindful): Guru memulai dengan “Mindful Listening” terhadap suara-suara di dalam dan luar kelas. Kemudian, meminta murid untuk menutup mata sejenak dan membayangkan diri mereka di keramaian (misalnya, di pasar, di mall). Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka rasakan? Mengapa orang-orang berinteraksi seperti itu? Ini untuk membangun kesadaran akan interaksi sosial.
- Apersepsi & Motivasi (Joyful & Meaningful): Guru menampilkan video singkat yang menunjukkan berbagai fenomena sosial yang menarik atau membingungkan (misalnya, flash mob, tren gaya hidup aneh, antrean panjang untuk sesuatu yang sepele, atau video tentang bullying di sekolah). Mengajukan pertanyaan pemantik: “Mengapa hal ini bisa terjadi?”, “Siapa yang bertanggung jawab?”, “Bagaimana kita bisa memahami pola-pola ini?”. Membangkitkan rasa ingin tahu tentang ilmu yang mempelajari masyarakat.
- Tujuan Pembelajaran: Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.
- Asesmen Diagnostik (Awal): Kuis singkat (Google Forms/Mentimeter) dengan pertanyaan seperti: “Menurutmu, apa itu masyarakat?”, “Apa yang dipelajari dalam ilmu sosial?”, “Sebutkan satu masalah sosial yang kamu ketahui!”. Untuk mengidentifikasi pengetahuan awal dan miskonsepsi.
Kegiatan Inti (Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi):
- Eksplorasi (Memahami): Guru membagi kelompok murid. Setiap kelompok diberikan beberapa definisi sosiologi dari para ahli yang berbeda (dicetak di kartu atau ditampilkan di slide).
- Diferensiasi Konten: Kelompok dengan tingkat pemahaman awal lebih tinggi dapat diberikan definisi yang lebih kompleks atau diminta untuk mencari definisi tambahan dari sumber lain.
- Murid diminta untuk menganalisis definisi tersebut, mencari kata kunci, dan mencoba merumuskan kesamaan atau perbedaan antar definisi.
- Konseptualisasi (Memahami): Guru menjelaskan secara interaktif pengertian sosiologi, objek kajiannya (masyarakat, interaksi sosial, gejala sosial), dan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, dilengkapi dengan contoh-contoh yang relevan dari kehidupan nyata (misalnya, contoh gejala sosial seperti kemacetan, tawuran, atau perubahan tren fesyen).
- Aplikasi (Mengaplikasi):
- Diferensiasi Proses:
- Kelompok 1 (Visual/Konseptual): Membuat infografis/peta konsep tentang definisi sosiologi dan objek kajiannya, disertai gambar contoh.
- Kelompok 2 (Auditori/Analitis): Memilih satu fenomena sosial di lingkungan sekolah (misalnya, kebiasaan murid saat jam istirahat, penggunaan gawai) dan menjelaskan bagaimana fenomena tersebut dapat menjadi objek kajian sosiologi.
- Kelompok 3 (Kinestetik/Role-Play): Melakukan simulasi singkat interaksi sosial tertentu (misalnya, proses negosiasi, konflik antar kelompok kecil) dan menjelaskan elemen-elemen sosiologis di dalamnya.
- Guru berkeliling membimbing, memberikan umpan balik, dan memastikan pemahaman konsep.
- Refleksi (Merefleksi): Murid menuliskan dalam buku catatan: “Setelah belajar sosiologi, saya melihat fenomena sosial ini dengan cara yang berbeda:…”, “Satu hal yang paling menarik dari objek kajian sosiologi adalah…”.
Kegiatan Penutup (Umpan Balik, Menyimpulkan, Perencanaan):
- Umpan Balik Konstruktif: Guru memberikan apresiasi terhadap hasil diskusi dan presentasi kelompok. Mengklarifikasi miskonsepsi umum tentang objek kajian sosiologi.
- Menyimpulkan Pembelajaran: Bersama murid, merangkum poin-poin penting tentang definisi sosiologi dan objek kajiannya.
- Perencanaan Pembelajaran Selanjutnya: Guru memberikan pengantar singkat tentang ciri-ciri dan fungsi sosiologi. Memberikan penugasan mandiri: mencari 2-3 berita tentang masalah sosial di Indonesia (misalnya, di Tegal dan sekitarnya) dan mencoba memikirkan, “Mengapa masalah ini bisa terjadi?”.
Pertemuan 2: Ciri-Ciri dan Fungsi Sosiologi
Kegiatan Pendahuluan (Mindful Learning, Joyful Learning):
- Review & Kesadaran (Mindful): Guru memulai dengan “Gallery Walk” singkat, menampilkan beberapa gambar/foto masalah sosial (dari berita atau lingkungan lokal). Meminta murid untuk merenungkan: “Apa yang kalian rasakan saat melihat gambar ini? Apa peran kita sebagai bagian dari masyarakat?”. Ini untuk membangun kepekaan sosial.
- Apersepsi & Motivasi (Joyful & Meaningful): Guru menampilkan kutipan dari seorang sosiolog terkenal (misalnya, “Sosiologi membuat yang aneh menjadi akrab, dan yang akrab menjadi aneh”). Mengajukan pertanyaan: “Apa maksud kutipan ini?”, “Bagaimana sosiologi bisa membantu kita memecahkan masalah di masyarakat?”. Membangkitkan rasa ingin tahu tentang kegunaan sosiologi.
- Tujuan Pembelajaran: Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.
Kegiatan Inti (Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi):
- Eksplorasi (Memahami): Murid dalam kelompok kecil mendiskusikan hasil penugasan mandiri mereka tentang berita masalah sosial. Guru memfasilitasi diskusi tentang “Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah masalah sosial, bukan masalah individu?”.
- Konseptualisasi (Memahami): Guru menjelaskan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu (empiris, teoretis, kumulatif, non-etis) dengan contoh penerapannya dalam penelitian sosial. Dilanjutkan dengan penjelasan fungsi sosiologi dalam berbagai aspek kehidupan (pembangunan, penelitian, pemecahan masalah, perencanaan sosial) menggunakan studi kasus nyata.
- Aplikasi (Mengaplikasi):
- Diferensiasi Produk (Proyek Mini):
- Tugas Utama: Setiap kelompok memilih satu masalah sosial yang relevan di lingkungan Tegal atau Indonesia (misalnya, masalah sampah, kemacetan, kurangnya partisipasi warga dalam kegiatan sosial, penyalahgunaan media sosial, atau bullying di sekolah). Mereka diminta untuk:
- Mengidentifikasi masalah tersebut dari sudut pandang sosiologi (bukan hanya dampak pribadi).
- Menganalisis bagaimana ciri-ciri sosiologi (misalnya, empiris, non-etis) relevan dalam memahami masalah ini.
- Merumuskan minimal 1-2 fungsi sosiologi yang dapat diaplikasikan untuk memahami/memecahkan masalah tersebut (misalnya, sebagai dasar kebijakan pembangunan, sebagai dasar penelitian untuk mencari akar masalah, atau sebagai evaluasi program sosial).
- Menyajikan hasil analisis dalam bentuk poster digital, infografis, atau presentasi singkat.
- Dukungan:
- Bagi kelompok yang kesulitan, guru dapat memberikan panduan pertanyaan atau contoh kerangka analisis.
- Bagi kelompok yang lebih mahir, dapat diminta untuk melakukan survei mini atau wawancara singkat untuk mendapatkan data awal.
- Guru membimbing setiap kelompok dalam proses pengerjaan proyek, fokus pada kemampuan murid menganalisis dan mengaplikasikan fungsi sosiologi.
- Refleksi (Merefleksi): Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka. Setelah presentasi, guru meminta murid untuk mengisi “Refleksi Warga Negara”: “Bagaimana pemahaman saya tentang sosiologi dapat membuat saya menjadi warga negara yang lebih baik dan peduli?”.
Kegiatan Penutup (Umpan Balik, Menyimpulkan, Perencanaan):
- Umpan Balik Konstruktif: Guru memberikan apresiasi atas ide-ide dan analisis murid dalam proyek. Menguatkan pentingnya peran sosiologi dalam memahami dan mengatasi masalah sosial.
- Menyimpulkan Pembelajaran: Guru memimpin diskusi untuk menyimpulkan ciri-ciri dan berbagai fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat.
- Perencanaan Pembelajaran Selanjutnya: Mengajak murid untuk terus peka dan menggunakan “kacamata sosiologi” dalam melihat fenomena di sekitar mereka.
|
| Asesmen Pembelajaran |
- Asesmen Awal Pembelajaran (Diagnostik):
- Tujuan: Mengukur pengetahuan awal murid tentang masyarakat, interaksi sosial, dan isu-isu sosial, serta mengidentifikasi minat dan gaya belajar.
- Format:
- Kuis Pra-Materi (Google Forms/Lisan):
- Contoh Pertanyaan: “Apa yang kamu pahami tentang ‘masyarakat’?”, “Sebutkan satu peristiwa di sekolah/lingkunganmu yang menurutmu menarik untuk diamati!”, “Apakah kamu peduli dengan masalah sampah di kotamu? Mengapa?”.
- Jamboard/Padlet: Meminta murid menuliskan “Apa yang ingin saya ketahui tentang Sosiologi?” atau “Satu kata tentang Masyarakat”.
- Diskusi Terbuka: Mengajukan pertanyaan pemantik tentang fenomena sosial yang sedang populer.
- Asesmen Proses Pembelajaran (Formatif):
- Tujuan: Memantau pemahaman murid selama proses pembelajaran, memberikan umpan balik berkelanjutan, dan menyesuaikan strategi pengajaran.
- Format:
- Observasi Partisipasi (Lampiran Rubrik Observasi): Guru mengamati keaktifan dalam diskusi, kualitas pertanyaan, kerja sama kelompok, dan kemampuan mengidentifikasi contoh-contoh fenomena sosial.
- Contoh Indikator:
- Menunjukkan rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan terkait fenomena sosial.
- Memberikan kontribusi yang relevan dalam diskusi kelompok.
- Mampu bekerja sama dalam menganalisis kasus.
- Menunjukkan kepekaan terhadap masalah sosial.
- Penilaian Kinerja Kelompok (Rubrik Penilaian Presentasi/Produk):
- Pertemuan 1: Penilaian infografis/peta konsep objek kajian sosiologi atau presentasi analisis fenomena di sekolah.
- Pertemuan 2: Penilaian hasil analisis kasus masalah sosial dan perumusan fungsi sosiologi.
- Contoh Kriteria:
- Kesesuaian dengan konsep yang dipelajari (definisi, objek, ciri, fungsi).
- Kreativitas dan kejelasan penyajian.
- Kerja sama tim.
- Kemampuan menjelaskan/mempresentasikan.
- Jurnal Refleksi: Murid menuliskan pemahaman, kesulitan, dan koneksi pribadi mereka dengan materi setiap akhir sesi.
- Kuis Singkat Lisan/Tertulis: Pertanyaan spontan atau kuis singkat untuk mengecek pemahaman konsep kunci di tengah pembelajaran.
- Asesmen Akhir Pembelajaran (Sumatif):
- Tujuan: Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan setelah materi selesai.
- Format:
- Penilaian Proyek Mini (Analisis dan Solusi Sosial):
- Tugas: Setiap kelompok menyerahkan produk (poster digital/infografis/presentasi video pendek) yang menganalisis satu masalah sosial lokal (misalnya, di Tegal) dari perspektif sosiologi dan mengusulkan bagaimana fungsi sosiologi dapat diterapkan untuk memahami atau memecahkan masalah tersebut.
- Rubrik Penilaian Proyek “Analisis dan Solusi Sosial”:
- Identifikasi Masalah & Objek Kajian (25%):
- Ketepatan dalam mengidentifikasi masalah sosial sebagai objek kajian sosiologi.
- Kemampuan melihat pola-pola sosial di balik masalah tersebut.
- Penerapan Ciri Sosiologi (25%):
- Jelas dalam menjelaskan bagaimana ciri sosiologi (empiris, non-etis, dll.) relevan dalam menganalisis masalah tersebut.
- Analisis Fungsi Sosiologi (30%):
- Ketepatan dalam merumuskan dan menjelaskan fungsi sosiologi (penelitian, pembangunan, pemecahan masalah) yang relevan dengan kasus.
- Kualitas usulan solusi/pendekatan sosiologis.
- Kreativitas & Komunikasi (20%):
- Tampilan produk menarik dan mudah dipahami.
- Penyampaian presentasi (jika ada) jelas dan meyakinkan.
- Kerja sama tim yang efektif.
- Tes Tertulis (Esai Analitis):
- Tugas: Murid diberikan sebuah studi kasus singkat tentang fenomena sosial kontemporer (misalnya, kasus “bullying” di sekolah, fenomena “cancel culture”, atau migrasi desa-kota). Mereka diminta untuk:
- Menjelaskan fenomena tersebut dari sudut pandang sosiologi (menggunakan konsep objek kajian).
- Menganalisis bagaimana ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan relevan dalam mempelajari fenomena tersebut.
- Merumuskan minimal dua fungsi sosiologi yang dapat diterapkan untuk memahami atau memberikan solusi terhadap fenomena tersebut.
- Contoh Pertanyaan:
- “Fenomena banyaknya remaja yang kecanduan game online dan kurang berinteraksi langsung menjadi sorotan di media massa. Jelaskan fenomena ini dari sudut pandang sosiologi. Bagaimana ciri-ciri sosiologi membantu kita memahaminya, dan fungsi sosiologi apa saja yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ini?”
|